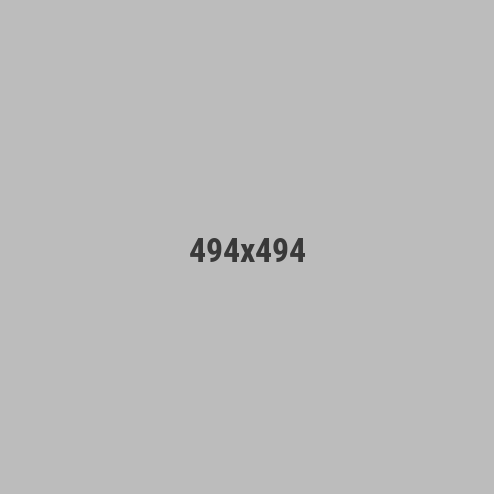
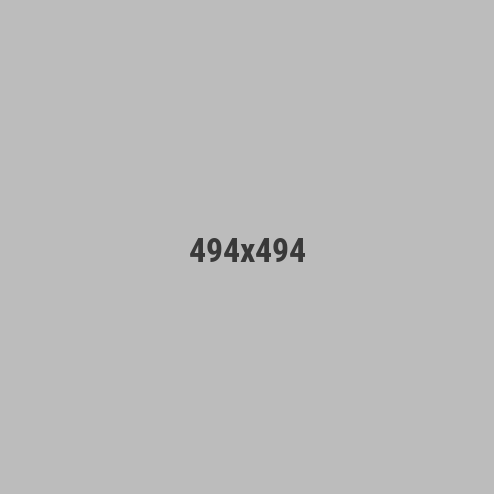

Ilustrasi gantung diri. Shutterstock/Freedom Studio
“Buat dia sadar kalau kita akan selalu ada buat dia, dan setia ngedengerin segala keluhannya.”
Dalam berbagai materi untuk menghadapi seseorang yang menunjukkan tendensi bunuh diri, imbauan tersebut sudah pasti kerap kita dengar dari sejumlah praktisi psikologi. Beragam pengetahuan untuk tindakan lebih lanjut mencegah individu melakukan bunuh diri, memang belakangan ramai diajarkan pada masyarakat lewat berbagai medium sosialisasi. Ada pula institusi, baik pemerintah maupun swasta, yang menangani hal ini.
Akan tetapi, ilmu terkait isu bunuh diri tersebut mayoritas umumnya berfokus pada pencegahan ketika tanda-tandanya telah terjadi. Misalnya, dengan menjadi pendengar yang baik bagi individu terkait, atau mengajak yang bersangkutan menghubungi pihak profesional untuk membantu mengatasi tekanan yang mendorongnya untuk bunuh diri.
Solusi untuk mencegah tindakan bunuh diri tersebut dilakukan dengan melihat niat bunuh diri secara lebih dekat dan mikro, yakni dengan melakukan studi dan pendekatan spesifik terhadap individu terkait. Kemudian, melakukan sejumlah tindakan yang dianjurkan untuk menahan gejolak untuk mengakhiri hidup.
Padahal, sebenarnya ada cara lain melihat isu bunuh diri ini dengan dari sudut pandang lebih luas dan makro. Ada pendekatan sosiologi yang mampu menempatkannya sebagai fakta sosial dan membedah faktor-faktor yang menjadi akar penyebabnya.
Fenomena Jadi Fakta Sosial
Besaran angka kasus bunuh diri membuatnya memang perlu mendapat perhatian lebih luas. Data World Health Organization (WHO) yang dipublikasikan pada 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 700.000 orang di dunia meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya.
Kemudian, secara khusus, isu bunuh diri juga menjadi urgensi bagi negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Ya, karena 77% kasus terjadi pada kelompok ini. Sayangnya, negara kita termasuk salah satunya.

WHO merangkum kasus-kasus bunuh diri ke dalam data dengan angka yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ini telah terjadi di berbagai belahan dunia secara konstan, sehingga menjadi indikasi bahwa ada kekuatan di luar individu yang menjadi penyebabnya.
Logika ini sejalan dengan perhatian Émile Durkheim, sosiolog asal Prancis, terhadap fenomena bunuh diri yang tidak terpaku pada kejadiannya sebagai suatu tindakan individu, melainkan pada besar dan turun-naiknya angka kasus. Artinya, ada sejumlah penyebab awal yang dapat dikelompokkan sebelum seseorang memutuskan bunuh diri, baik dengan memberikan tanda-tanda kepada lingkungan sekitarnya ataupun tidak.
Durkheim yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Modern, melihat fenomena bunuh diri sebagai fakta sosial, alih-alih sebagai fakta individu. Dan sebagai fakta sosial, sosiolog ini memandang bahwa bunuh diri dipengaruhi oleh fakta sosial lainnya.
Menurutnya, fakta sosial pemicu tersebut adalah ketidakseimbangan keadaan dalam lingkungan sosial masyarakat, yakni tingkat integrasi sosial dan tatanan nilai/norma pada masyarakat.
Ada kalanya, integrasi sosial dan tatanan nilai/norma dalam masyarakat berfungsi terlalu kuat ataupun terlalu lemah. Hal inilah yang berpotensi memberikan tekanan kepada individu dalam masyarakat.
Dengan kata lain, sebagai akibat dari terlalu beratnya tekanan yang dirasakan, bunuh diri menjadi salah satu jalan keluar yang dipilih.
Individu Sebagai Kelompok Masyarakat
Faktor pertama yang menurut Durkheim kekuatannya memengaruhi motivasi seseorang untuk bunuh diri adalah integritas sosial. Hal ini mengacu pada hubungan individu dengan lingkungan masyarakat tempatnya berada. Potensi bunuh diri dapat mencuat ketika terjadi ketidakseimbangan pada faktor ini.
Ketika integritas sosial terlalu lemah, dapat terjadi yang disebut egoistic suicide. Yakni fenomena bunuh diri yang terjadi setelah individu tersebut harus berkutat dengan tekanan hidup seorang diri karena minimnya kekuatan hubungan dengan masyarakat sekitarnya.
Tak dimungkiri, isu kesehatan mental yang dapat ditinjau dari perspektif psikologis berpotensi jadi penyebab tekanan pada diri seseorang. Begitu juga dengan tekanan masalah lain yang berasal dari luar diri individu tersebut. Kedua hal ini kemudian dapat berdampak buruk jika dihadapkan dengan lemahnya hubungan dirinya dengan lingkungan.
Integritas sosial yang lemah dalam bermasyarakat menyebabkan seseorang enggan membagi beban permasalahannya dengan sosok lain. Di sisi lain, masyarakat pun merasa kurang tergugah untuk mencampuri urusan individu tersebut karena minimnya simpati akibat renggangnya hubungan.
Sejumlah kasus egoistic suicide cukup sering ditayangkan dalam pemberitaan di layar kaca. Misalnya, ketika terdapat jenazah yang baru ditemukan berminggu atau berbulan setelah kematian di kediaman sendiri. Masyarakat tidak mencoba mencari tahu apa yang terjadi, dan individu pun tidak berusaha mencari pertolongan sehingga akhirnya menyerah dalam mempertahankan hidup.
Tetapi jangan salah. Potensi bunuh diri dapat juga terjadi ketika integritas sosial terlalu kuat. Bunuh diri jenis ini dinamakan altruistic suicide oleh Durkheim. Hal ini terjadi ketika ikatan dengan masyarakat atau elemennya terlalu intim sehingga individu tersebut merasa perlu melakukan pengorbanan.
Kasus bunuh diri Marlia Hardi, seorang selebritas ternama pada era 1970-an dapat dikategorikan sebagai altruistic suicide. Sosok perempuan yang lekat dengan sejumlah karakter bijaksana ini ditemukan oleh sopir pribadinya dalam keadaan tak bernyawa di kediaman sendiri. Kasus tersebut disimpulkan sebagai bunuh diri setelah ditemukan sejumlah surat wasiat yang ditinggalkan Marlia.
 Aktris lawas Marlia Hardi yang meninggal karena bunuh diri. Sumber: wikimedia
Aktris lawas Marlia Hardi yang meninggal karena bunuh diri. Sumber: wikimedia Dari surat-surat tersebut terbongkar depresi yang dialami Marlia Hardi akibat terlilit banyak utang, baik kepada sejumlah rentenir ataupun sosok-sosok lainnya. Usut punya usut, kegiatan arisan call yang kala itu sedang jadi tren di kalangan sosialita jadi biang keroknya.
Dalam sebuah perkumpulan selebritas yang berjumlah 135 anggota, kepopuleran Marlia membuat dirinya dipercaya sebagai bandar arisan call. Namun, di balik gelar pemimpin komunitas, ada tanggung jawab besar yang harus diembannya, yakni menalangi anggota yang belum membayar setoran.
Bermula dari sejumlah anggota yang tak kunjung membayar setoran bulanan, Marlia harus menggunakan uang pribadinya untuk menutupi kekurangan pembayaran pemenang arisan. Kondisi semakin parah dan membuat dirinya harus banyak berutang dan jatuh dalam depresi, hingga akhirnya memutuskan bunuh diri.
Seperti pada kasus Marlia Hardi, pada fenomena altruistic suicide, individu enggan meminta pertolongan dan cenderung menyembunyikan tekanan yang dirasakan dari keluarga maupun orang-orang terdekat. Bunuh diri diartikan sebagai bentuk pengorbanan yang dinilai sebagai produk kelekatan dirinya dengan kelompok masyarakat.
Pentingnya Nilai dan Norma yang Dinamis
Selain integritas sosial, Durkheim juga menitikberatkan kekuatan nilai/norma sebagai hal yang perlu dijaga keseimbangannya demi menekan penetrasi kasus bunuh diri. Potensi terjadinya bunuh diri dapat tercipta jika tatanan nilai/norma dalam suatu masyarakat terombang-ambing dan goyah. Namun bisa juga jika tatanan nilai/norma tersebut terlalu kuat atau ajek.
Saat nilai/norma mengalami goncangan yang mengakibatkannya terombang-ambing, potensi yang terjadi adalah anomie suicide. Goncangan yang terjadi pada masyarakat, atau pada tatanan yang lebih luas seperti negara atau bahkan dunia, mengakibatkan kehidupan individu ikut goyah. Contoh yang sangat membekas adalah apa yang terjadi saat Covid-19 mulai menyerang pada awal 2020.
Direktur Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan Vensya Sitohang mengungkapkan bahwa kondisi pandemi tersebut berdampak buruk pada kesehatan jiwa. Kondisi pandemi yang memaksa semua orang terbatas dalam beraktivitas yang mengakibatkan tekanan yang lebih besar dalam masyarakat.
Banyak bisnis bertumbangan karena pembatasan sosial. Korban kekerasan rumah tangga terpaksa menjadi makin dekat dengan pelakunya. Dan, penderita masalah fisik mengalami depresi karena sulit mengakses layanan kesehatan. Sebagai akibat, psikiater Hervita Diatri bahkan menuturkan terjadinya peningkatan jumlah individu yang memikirkan untuk bunuh diri (Kemenkes, 2022).
Pada lima bulan awal pandemi, hasil survei memperlihatkan bahwa ada 1 dari 5 orang Indonesia pada rentang usia 15-29 tahun yang terpikir untuk mengakhiri hidup. Ironi, angka ini meningkat setelah setahun pandemi berjalan, menjadi 2 dari 5 orang. Lebih kritisnya, pada awal 2022, probabilitasnya kembali meningkat menjadi 1 dari 2 orang.

Di sisi lain, tatanan nilai/norma yang terlalu ajek dan kaku dalam masyarakat juga dapat melahirkan potensi bunuh diri, yakni fatalistic suicide. Fenomena ini biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki budaya tertentu, terutama yang bersifat hierarkis, pada jangka waktu yang sangat lama dan tak tergoyahkan.
Contoh dari bunuh diri jenis ini dapat terjadi pada masyarakat di era perbudakan, di mana ada kelompok budak yang memang harus menuruti apa pun yang diminta tuannya. Pembatasan antara budak dan tuannya sangat jelas, sehingga potensi tatanan nilai untuk berubah sangat kecil. Kemungkinan yang sangat kecil untuk mengubah nasib membuat budak hanya dapat pasrah dan menyerah dengan hidupnya.
Kini, meski era perbudakan tradisional sudah terlewati, sejumlah bentuk perbudakan di masa modern masih terjadi. Penyalahgunaan wewenang kerap dilakukan dalam bungkus tertentu oleh kelompok yang memiliki kuasa terhadap kelompok marginal. Tak ayal, depresi berujung upaya mengakhiri hidup pun masih menghantui sejumlah kelompok masyarakat.
Memutus Akar Permasalahan
Dari empat jenis bunuh diri yang dikelompokkan oleh Émile Durkheim – baik egoistic suicide, altruistic suicide, anomie suicide, maupun fatalistic suicide – minimnya mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi depresi dan tekanan mungkin memang jadi penentu terjadinya tindakan. Namun, yang juga perlu digarisbawahi adalah bahwa ada penyebab di balik depresi apa pun.
Melalui pengetahuan dari perspektif psikologi, masyarakat dapat terbantu dan terlatih untuk mencegah tindakan bunuh diri di sekitar mereka. Akan tetapi, pendekatan ini umumnya hanya menjadi bentuk penanggulangan ketika individu telah menunjukkan tanda-tanda ingin mengakhiri hidup.
Tanda-tanda yang ditunjukkan tersebut merupakan hasil dari faktor lain yang menjadi pendorong yang menjadi akar depresi. Dengan memutus akar permasalahan, tanda maupun tindakan yang menunjukkan potensi bunuh diri tidak memiliki kesempatan terjadi atau bertumbuh. Dan tentunya, hanya dengan temukan akar permasalahan, kita dapat temukan solusi paling efektif
Makanya, menjadi penting pula untuk memutus akar penyebab dari tindakan bunuh diri, yakni dengan melihat fenomena ini sebagai fakta sosial yang lebih besar. Bagaimana caranya?
Salah satunya, dengan mendorong tatanan atau institusi/pemangku kepentingan yang lebih besar, misalnya pemerintah untuk ikut turun tangan. Misalnya, dengan merumuskan kebijakan atau program yang mengatur dan bertujuan menciptakan masyarakat dengan hubungan integritas yang seimbang – tidak terlalu kuat ataupun terlalu lemah – antara individu dengan lingkungan masyarakat tempatnya hidup. Hal tersebut untuk mengurangi potensi egoistic suicide dan altruistic suicide.
Sementara itu, untuk meminimalkan kemungkinan anomie suicide dan fatalistic suicide, penting bagi tatanan atau institusi/pemangku kepentingan yang lebih besar untuk menjaga iklim norma/nilai yang seimbang dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu membatasi tekanan pada individu di dalamnya.
Pada akhirnya, fenomena bunuh diri tetap menjadi isu yang patut mendapat perhatian karena telah menjadi fakta global. Berbagai cara perlu dilakukan sebagai pencegahan, baik melalui pendekatan psikologis maupun sosiologi, baik dari tataran individu dan kelompok masyarakat, hingga regional, nasional, dan bahkan global.
Pertanyaannya, sudah sejauh apa upaya yang dilakukan? Kemudian, apakah kita sudah jadi salah satu solusinya? Mari kita kembali berkaca.
Referensi
BiCo Story. (2022, Januari 2). Marlia Hardi dan Jerat Arisan MAUT - Cerita Bergambar - https://www.youtube.com/watch?v=mGk4_ojek5E
Durkheim, É. (195). Suicide: A Study in Sociology. New York: The Free Press.
Kemenkes. (2022, Mei 14). Pandemi COVID-19 Memperparah Kondisi Kesehatan Jiwa Masyarakat. Retrieved from Kementerian Kesehatan: https://www.kemkes.go.id/article/view/22051400004/pandemi-covid-19-memperparah-kondisi-kesehatan-jiwa-masyarakat.html
World Health Organization. (2023, Agustus 28 ). Suicide. Retrieved from World Health Organization https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide