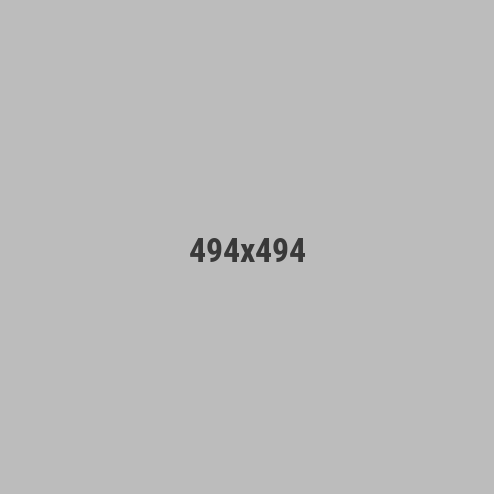
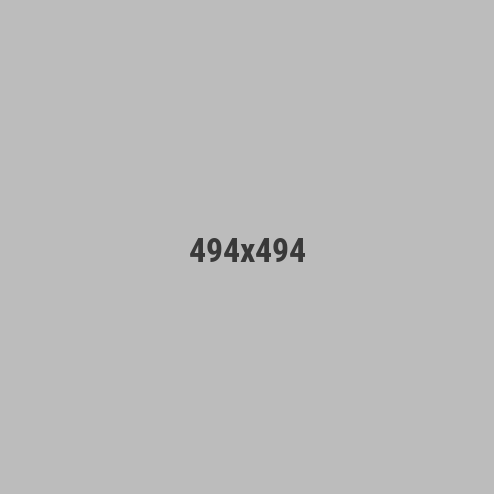

Ilustrasi Biodiesel Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca. Shutterstock/EVANATTOZA
Energi adalah kebutuhan dasar manusia yang sejak dahulu hingga masa depan akan terus diupayakan pemenuhannya. Semenjak terjadinya revolusi industri, serta seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, permintaan kebutuhan energi di seluruh dunia terus mengalami peningkatan. Hal ini, pada akhirnya, memaksa manusia untuk terus melakukan diversifikasi bentuk energi, khususnya fosil.
Dalam perjalanannya, ternyata penggunaan jenis energi fosil dinilai telah menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap lingkungan.
Peningkatan emisi gas rumah kaca (Green House Gas emission), ditengarai merupakan salah satu dampak atas eksploitasi jenis energi fosil, terutama minyak bumi dan batu bara yang berlebihan. Emisi gas rumah kaca adalah proses energi panas matahari yang diterima oleh atmosfer lebih banyak dibanding panas yang dilepas kembali ke angkasa (Abdullah dan Khairuddin, 2009).
Bahan Bakar Nabati
Sebagai upaya konservasi energi dan pemenuhan kebutuhan energi bersih serta ramah lingkungan, salah satu cara yang ditempuh adalah mengembangkan Bahan Bakar Nabati (BBN), atau yang juga sering disebut dengan biofuel. Terminologi biofuel ini digunakan baik untuk menyebut biofuel cair (liquid biofuel) maupun energi biomassa (Howarth et al., 2009).
Secara teori, pengembangan BBN atau biofuel ini dapat diperoleh dengan melakukan fermentasi dari sari pati berbagai jenis tanaman. Proses fermentasi ini menghasilkan minyak nabati (biofuel) yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan energi lainnya pengganti bahan bakar fosil.
Beberapa jenis tanaman yang selama ini telah banyak dicoba untuk dikembangkan sebagai sumber BBN ini adalah tebu (molasses), singkong, ubi jalar, grains (jagung/maize, gandum, sorghum, beras). Ada beberapa jenis limbah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai BBN, antara lain ialah limbah agrikultural, seperti: grain stalk, rice hulls, cassava peels & pulp, limbah pabik kelapa sawit, limbah kehutanan, misalnya wood-chips, saw dust, limbah organik, limbah kota dan biomassa umum yaitu daun; batang dan lain lain (Puradinata, 2012).
Biodiesel
Belakangan, salah satu jenis BBN yang banyak dikembangkan adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat menyerupai minyak diesel/solar (Subekti dan Djaohar, 2007: 54). Di Indonesia, pengembangan biodiesel dimulai pada tahun 1996, yang dilakukan oleh Lemigas. Mereka melakukan pencampuran antara biodiesel dan minyak solar dengan rasio 30:70.

Ketika itu, Lemigas bekerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti Penerapan teknologi (BPPT), Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB), melakukan sejumlah penelitian biodiesel dari berbagai jenis bahan baku. Beberapa bahan baku tersebut ialah kelapa sawit, minyak jelantah, jarak pagar dan minyak nabati lainnya. Riset yang dilakukan tidak hanya riset-riset dasar namun juga produksi skala pilot, hingga uji coba pada mesin (Litbang ESDM, 2021).
Khusus dalam memproduksi biodiesel ini, ada suatu proses kimia yang disebut reaksi transesterifikasi atau esterifikasi, dilakukan. Proses ini adalah reaksi senyawa ester dan alkohol dengan menggunakan suatu katalisator. Selain minyak nabati seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahan baku juga bisa dari lemak hewani, lemak bakas atau lemak daur ulang. Semua bahan baku ini mengandung trigliserida, asam lemak bebas (ALB), dan pencemar (Devita, 2015).
Selain dari berbagai jenis bahan baku utama tersebut, bahan baku lain yang diperlukan dalam pembuatan biodiesel adalah alkohol. Alkohol pada umumnya digunakan sebagai pereaksi untuk minyak nabati adalah methanol. Meski demikian, bahan lain yang juga dapat digunakan ialah isopropanol atau butil. Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah kandungan air dalam alkohol. Kandungan air yang tinggi akan menghasilkan biodiesel dengan kualitas rendah karena kandungan sabun, ALB dan trigliserida tinggi.

Lebih lanjut, dalam proses pembuatan biodiesel tersebut dibutuhkan katalis. Katalis diperlukan karena alkohol larut dalam minyak. Katalisator yang digunakan umumnya bersifat basa kuat, yaitu natrium hidroksida (NaOH), kalium hidroksisa (KOH), dan natrium metoksida.Katalisator yang dipilih tergantung pada minyak nabati yang digunakan.
Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai salah satu jenis EBT secara lebih luas kemudian juga didukung oleh sejumlah kebijakan pemerintah. Kelebihan biodiesel dibandingkan minyak diesel yang sepenuhnya berasal dari fosil, menjadikan penguat dasar kebijakan dikeluarkan. Beberapa kelebihan biodiesel antara lain ialah dapat diproduksi secara lokal dengan memanfaatkan sumber minyak/ lemak alami yang tersedia, proses produksi dan penggunaannya bersifat lebih ramah lingkungan dengan tingkat emisi CO, NO dan sulfur dan senyawa hasil pembakaran lainnya rendah, dan lebih mudah terurai di alam.
Pengembangan Tanaman Lain
Penggunaan biodiesel juga dapat mereduksi polusi tanah serta melindungi kelestarian perairan dan sumber air minum. Dalam penggunaan biodiesel juga tidak diperlukan modifikasi mesin. Hal ini dikarenakan biodiesel mempunyai efek pembersihan terhadap tangki bahan bakar, injektor dan slang, tidak menambah efek rumah kaca karena karbon yang dihasilkan masih dalam siklus karbon (Devita, 2015).
Salah satu momentum penting dalam perkembangan biodisel adalah pilot plant pembangunan biodiesel berbahan baku sawit (CPO) yang didesain di Riau pada tahun 2003. Besaran kapasitasnya sebesar 3 ton per hari. Pabrik ini memanfaatkan CPO parit dari berbagai kebun milik PTPN di daerah Riau. Pabrik ini sendiri akhirnya mulai dibangun pada tahun 2005 di daerah Kampar, Riau.
Setahun setelah berdirinya pabrik biodiesel tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan. Ada dua yang dikeluarkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006. Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut pengembangan biodiesel tidak hanya terbatas pada satu jenis bahan baku. Salah satu yang juga coba dikembangkan adalah yang berasal dari tanaman jarak pagar.
Tanaman jarak pagar pada dasarnya merupakan jenis tanaman semak (shurb). Tinggi rata-rata tanaman ini dapat mencapai 6 meter. Tanaman ini hidup di daerah tropis dan subtropis. Karenanya, tanaman ini banyak tersebar di Amerika, Asia dan Afrika. Sebaran tanaman jarak pagar di Indonesia banyak ditemukan di NTB dan NTT sebagai tanaman liar. Namun di beberapa daerah di NTB seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Bima, sudah dibudidayakan oleh masyarakat
Kementerian Pertanian ketika itu kemudian juga ditugaskan untuk mengembangkan tanaman yang digunakan untuk biodiesel melalui Direktorat Tanaman Tahunan. Pengembangan dilakukan di berbagai daerah yang dianggap berpotensi, seperti NTB dan NTT. Selain itu, Puslitbang Perkebunan juga telah melakukan riset berbagai tanaman untuk biodiesel. Riset jarak pagar pertama di lakukan di Parung Kuda (Sukabumi), dan dilanjutkan di Pati, Jawa Tengah dan Asembagus di Jawa Timur (Litbang ESDM, 2021).
Ada juga kelebihan tanaman ini. Kadar CO2, SO2 dan CO yang dihasilkan dari pengembangan biodiesel dari minyak jarak sebagai bahan pencampur solar menunjukan adanya penurunan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Havendri (2008) menyebutkan bahwa, penurunan kadar CO2, SO2 dan CO terjadi pada putaran 1600 rpm dan 1800 rpm.
Jika melihat kadar minyak bijinya, hasil studi uji coba yang dilakukan oleh Santoso et al. (2011) di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa tingkat persentase kadar minyak jarak mencapai 40-47%. Hasil ini dibedakan antara tanaman asal tegakan alami dengan tanaman hasil budidaya.
Tanaman hasil budidaya memiliki tingkat kadar minyak yang relatif lebih tinggi dibandingkan tanaman alami di masing-masing wilayah ujicoba. Tetapi, hasil tersebut juga tergantung pada kondisi lahan. Semakin kering kondisi wilayah asal genotipe, maka kandungan minyak biji juga cenderung tinggi.
Namun, pengembangan biodiesel dari minyak jarak pagar tidak dapat diteruskan. Hal ini mengingat tingkat keekonomiannya yang rendah. Di beberapa daerah yang dikembangkan sebagai desa mandiri energi berbasis minyak jarak, juga mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena faktor perbedaan iklim yang menyebabkan produktivitas tanaman jarak rendah.
Dilihat dari cara pembudidayaannya, tanaman jarak pagar (jatropha curcas) akan tumbuh optimal pada lahan kering dataran rendah beriklim kering. Ketinggian lahan antara 0-500 meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan 300-2380 mm per tahun, dengan suhu 20-26⁰C (Hambali dan Mujdalipah, 2008).
Tanaman ini juga dapat tumbuh di lahan marginal yang miskin hara, namun memiliki drainase dan aerasi yang baik. Meski demikian, sebagaimana layaknya tanaman lainnya, tanaman jarak pagar akan optimal produksinya jika ditanam di lahan yang subur, khususnya pada tanah yang mengandung pasir 60-90%, dengan pH tanah 5,5-6,5; diberi pupuk yang cukup, dan tersedianya air pada musim kemarau.
Salah satu kelemahan jarak pagar ini ialah, meski butuh air, tetapi tanaman ini peka terhadap drainase yang buruk dan butuh klimat tegas antara musim hujan dan kemarau. Kemampuan daya serap karbondioksida mencapai 1,8 kg/kg bagian kering tanaman dari atmosfer.
Berbagai kondisi inilah yang menyebabkan pengembangan biodiesel di Indonesia lebih banyak berbasis pada minyak sawit. Apalagi sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, keberadaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel dapat dikatakan cukup berlimpah di Indonesia.
Dalam pengembangan biodiesel secara komersial dan massal, terdapat beberapa perusahaan yang menjadi pelopornya. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya ialah PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Indo Biofuels Energy dan PT Sumi Asih. Ketiga perusahaan ini bahkan sebenarnya telah mengembangkan biodiesel jauh sebelum mandatori biodiesel dikeluarkan oleh pemerintah.
PT Eterindo Wahanatama Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, industri biodiesel dan perdagangan produk kimia. Perusahaan ini telah melakukan penelitian dan pengembangan biodiesel semenjak tahun 2002. Selanjutnya di tahun 2005 perusahaan ini membangun pabrik biodiesel di Gresik Produk yang dihasilkan adalah Fatty Acid Metyl Ester. Awalnya, pabrik biodiesel yang dibangun memiliki kapasitas terpasang sebesar 70.000 MT/tahun, kemudian ditingkatkan menjadi 140.000 MT/tahun pada November 2012(Litbang ESDM, 2021).
PT Indo Biofuels Energy (IBE) didirikan di Merak, Banten pada tahun 2005. Pada awalnya, pabrik biodiesel yang dibangun PT IBE direncanakan untuk memproduksi biodiesel berbahan baku jarak pagar dengan kapasitas 20.000 KL/tahun. Namun ketidakcukupan feedstock dalam hal ini jarak pagar menjadi kendala utama. Sehingga di tahun 2006 diputuskan beralih menggunakan bahan baku sawit (CPO).
Sedangkan PT Sumi Asih yang berlokasi di Bekasi, memproduksi biodiesel pada tahun 2006 dengan kapasitas produksi biodiesel sebesar 3.000 ton/bulan, kemudian ditingkatkan menjadi 5.200 ton/bulan sehingga total kapasitas biodiesel mencapai 8.200 ton per bulan atau sekitar 100.000 ton per tahun. Produk-produk biodiesel dari perusahaan ini ahkan telah diekspor ke beberapa negara(Litbang ESDM, 2021).
Gas Rumah Kaca
Ada kelebihan dari biodisel, tentunya. Dilihat dari aspek lingkungan, menurut Subekti dan Djaohar (2007), biodiesel menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik, yaitu: bebas sulfur, bilangan asap (smoke number) yang rendah, memiliki cetane number yang lebih tinggi sehingga pembakaran lebih sempurna (clear burning), memiliki viskositas tinggi, sehingga mempunyai sifat pelumasan yang lebih baik untuk memperpanjang umur pakai mesin, serta dapat terurai (biodegradable).
Baca: Mandatory Biodiesel Berhasil Tekan 27,8 CO2e Emisi GRK
Jika dilihat dari rasio net balance, maka minyak kelapa sawit sebagai bahan biodiesel dinilai memiliki rasio net energy balance potensial paling tinggi dibandingkan berbagai jenis tanaman lainnya. Net energy balance ratio adalah rasio output energi yang digunakan dibagi dengan input bahan bakar fosil yang dibutuhkan untuk memproduksi energi.
Semakin tinggi rasio net energy balance suatu jenis tanaman, maka akan semakin rendah penggunaan bahan bakar fosil yang digunakan dalam pengolahan biofuel tersebut. Dengan demikian, efek gas rumah kaca yang dihasilkan juga akan semakin rendah (Howarth et al. 2009).
Menurut Santoso (2018) konsumsi biodiesel dari minyak sawit mencapai 2,57 juta kiloliter pada tahun 2017. Konsumsi ini diperkirakan berkontribusi sebesar 6,89 juta tCO2eq dalam penurunan emisi GRK. Bahkan, dengan semakin meningkatnya konsumsi biodiesel, diperkirakan hingga tahun 2030 penurunan emisi GRK akan meningkat rata-rata sekitar 5% per tahun.
Laporan IEA (2022) lebih menegaskan peran biofuel. Jenis bahan bakar ini disebut mempunyai peran yang signifikan dalam jangka pendek untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi. Bahkan, pasca 2030, tingkat penggunaan biofuel yang lebih tinggi di bidang transportasi menghasilkan pengurangan emisi dua kali lebih besar dari tingkat pengurangan emisi dari mobil listrik, yang penerapannya lebih lambat.
Namun, pada tahun 2050, seiring dengan meningkatnya daya saing kendaraan listrik dan terbatasnya pasokan biofuel termasuk salah satunya biodiesel, diharapkan akan berkontribusi hampir 5% terhadap pengurangan emisi. Meski ada kendaraan listrik, penggunaan biofuel secara luas tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap keseimbangan energi nasional dan penurunan emisi GRK nasional maupun global.
Referensi:
Abdullah dan Khairuddin. (2009). “Emisi Gas Rumah Kaca dan Pemanasan Global”, Jurnal Biocelebes, Vol.3 Juni 2009.
Mujdalipah, S., & Hambali, E. (2008). Teknologi bioenergi, biodesel, bioetanol, biogas, pure plant oil, biobriket dan bio-oil. Agro Media Pustaka, Jakarta.
Puradinata, D.S. (2012). Pembelajaran Interorganisasional dan Penciptaan Pengetahuan Dalam Pengembangan Bioethanol di Indonesia (Sebuah Pendekatan Soft System Methodology di PT Medco Ethanol Lampung), Disertasi FISIP UI Program Studi Ilmu Administrasi, Depok, tidak dipublikasikan
Devita, L. (2015, November). Biodiesel Sebagai Bioenergi Alternatif. Agrica Ekstensia, 9(2).
Subekti, et.al. (2007). “Biodiesel dan Bioethanol: Solusi Kelangkaan Energi Transportasi Indonesia”. Pevote, Vol 2. No.203, April-September 2007: 47-56, Jakarta, FT UNJ
Havendri, Adly. (2008). “Kaji Eksperimental Prestasi Dan Emisi Gas Buang Motor Bakar Diesel Menggunakan Variasi Campuran Bahan Bakar Biodiesel Minyak Jarak (Jatropha Curcas L) Dengan Solar”, dalam Teknika No.29 Vol.1 Thn XV April 2008, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya.
Howarth R.W, et al. (2009). dalam Howarth, RW and Stefan Bringezu (ed), Biofuels: Enviromental Consequences and Interactions with Changing Land Use, SCOPE Rapid Assessment, New York, Cornell Ithaca
[IEA] International Energy Agency. 2022. An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia. International Energy Agency, Prancis.
Santoso, I. (2018, Agustus). Potensi dan pengembangan bioenergi di Indonesia. IndoEBTKE Connex 2018. APROBI.