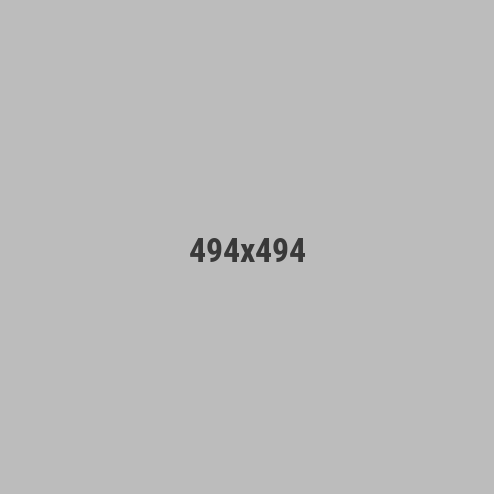
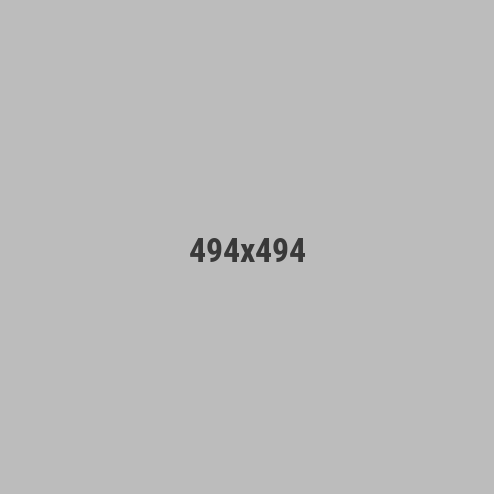

Spesies Harimau Jawa. Shutterstock/Ajie hari
Panthera tigris sondaica atau biasa disebut harimau Jawa merupakan subspesies harimau yang telah punah yang beradaptasi dan berevolusi di Pulau Jawa. Hewan tersebut merupakan salah satu dari tiga subspesies harimau yang ada, atau pernah hidup di Indonesia. Ketiga subspesies tersebut meliputi harimau jawa, harimau bali, dan harimau sumatra.
Namun, tahukah kalian bahwa dari ketiga subspesies harimau tersebut, hanya harimau Sumatra yang masih ada di Indonesia? Bahkan, statusnya saat ini terancam punah (critically endangered).
Oleh sebab itu, berdasarkan Permen LHK Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, harimau Sumatra ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.
Karakteristik Harimau Jawa
Bila dibandingkan dengan subspesies harimau di berbagai dunia, harimau Jawa memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada rata-rata harimau lainnya. Berat badannya hampir mencapai 310 pon. Hal tersebut sebagai bentuk evolusi dan adaptasi hewan tersebut terhadap ukuran mangsa mereka di alam liar yang relatif lebih kecil dibandingkan ukuran tubuh harimau jawa sendiri.
Harimau Jawa memiliki corak garis-garis hitam yang lebih sempit dan jarak tiap garis yang lebih rapat. Lebih lanjut, mereka memiliki kumis yang lebih panjang di antara subspesies harimau manapun.
Mangsa utama harimau Jawa adalah babi hutan dan rusa. Mereka cenderung memilih mangsa yang memiliki ukuran tubuh paling besar di alam liar.
Kolonialisme dan Kepunahan
Penyusutan populasi harimau Jawa dalam waktu cepat terjadi seiring dengan masuknya senjata api ke tanah air pada massa kolonialisme Belanda. Pada masa tersebut, perburuan harimau lebih banyak dilakukan dengan menggunakan senjata api. Penggunaan senjata api dalam perburuan harimau menyebabkan jumlah kematian harimau menjadi lebih signifikan.
Menurut Lombard (1996: 25) pada bukunya yang berjudul Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan, perburuan hewan buas di Pulau Jawa, termasuk harimau telah dilakukan sejak abad ke-17. Pada 1694, diberitakan seorang Belanda bernama Kapten Winkler telah menembak seekor harimau di sekitar lapangan Kasteel Batavia. Lalu pada 1829, pihak Belanda melakukan perburuan hewan buas di pantai utara, tidak jauh dari Pekalongan. Hasilnya, terbunuh tiga ekor badak dan tujuh ekor banteng sekaligus.
Perluasan wilayah perkebunan hingga ke hutan-hutan sejak tahun 1800 hingga 1900-an semakin memperparah keadaan. Belanda menginisiasi pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan secara besar-besaran di Pulau Jawa.
Hal tersebut menyebabkan harimau Jawa kehilangan habitat dan luas jelajah harimau yang semakin sempit. Akibatnya, banyak harimau yang keluar hutan untuk mencari makan. Tak jarang hewan buas ini berserobok dengan manusia, dan kemudian ini mendorong pemerintah Belanda menetapkan harimau Jawa sebagai binatang buruan yang harus dimusnahkan.
Rampogan Macan dan Fase Kepunahan
Selain faktor asing, ada juga adat budaya yang relevan dengan kepunahan harimau. Rampogan Macan adalah upacara adat yang melibatkan pertarungan antara harimau dengan manusia di Pulau Jawa.
Pada mulanya, tradisi tersebut biasa dimainkan di alun-alun dekat dengan keraton yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pertarungan yang melibatkan harimau dengan kerbau dan banteng. Kedua, pertarungan antara harimau dengan ratusan hingga ribuan manusia bersenjata tombak.
Seiring dengan perkembangannya, tradisi tersebut meluas ke beberapa daerah di Pulau Jawa dengan hanya memainkan bagian kedua, yakni pertarungan antara harimau dengan manusia.
Sebelum Rampogan Macan berlangsung, disiapkan sejumlah kandang kecil yang masing-masing berisi seekor harimau dan tiga hingga empat baris penombak diposisikan di sekeliling alun-alun. Kemudian satu kandang dibuka, lalu harimau berlari meninggalkan kandang untuk mencari celah di antara barisan para penombak. Biasanya harimau ditangkap dengan ujung tombak dan dilempar ke belakang. Hal tersebut diulangi sampai harimau tersebut mati.
Prosedur yang sama juga dilakukan pada harimau lain. Kadang kala, ada seekor harimau yang berhasil melarikan diri.
Awalnya, Rampogan Macan merupakan sebuah upacara adat yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Namun, adanya perubahan persepsi masyarakat yang menjadikan tradisi tersebut sebagai sebuah hiburan, sehingga Rampogan Macan dilaksanakan menjadi lebih rutin dan tak jarang disuguhkan untuk menyambut tamu.
Kedua hal di atas berpengaruh terhadap jumlah harimau. Pada 1940, harimau Jawa diperkirakan masih berjumlah 200 hingga 300 ekor. Namun, populasi penduduk di Pulau Jawa yang terus meningkat dengan dibarengi peningkatan kebutuhan terhadap komoditas pertanian dan perkebunan mendorong masyarakat untuk membuka hutan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hal tersebut semakin menciptakan konflik antara harimau dan manusia.
Harimau Jawa terpaksa punah karena perburuan, keracunan, dan penggundulan hutan. Pada tahun 1950'an, diperkirakan hanya ada sekitar 20 hingga 25 ekor harimau yang tersisa di hutan-hutan Pulau Jawa.
Pada 1974, jumlah harimau jawa di Taman Nasional Meru Betiri diperkirakan ada tiga hingga empat ekor. Kemudian, penampakan harimau Jawa terakhir yang terkonfirmasi terjadi pada 1976 di Taman Nasional Meru Betiri. Setelah itu, beberapa kali terdapat laporan mengenai kemunculan harimau Jawa. Namun, karena kurangnya bukti yang valid, kemunculan hewan tersebut tidak bisa dikonfirmasi.
Akhirnya pada 2003, International Union for Conservation of Nature (IUCN) secara resmi mengumumkan bahwa harimau Jawa dinyatakan punah.
Kepunahan harimau Jawa tentunya memberikan kesedihan bagi kita rakyat Indonesia. Namun, hal tersebut harusnya menjadikan kita untuk lebih peduli kepada sesama makhluk hidup.
Jangan lupa, bahwa Indonesia saat ini masih memiliki satu subspesies harimau lain yang juga harus dilindubgi, yaitu harimau Sumatra. Oleh karena itu, menjadi tugas kita semua agar harimau Sumatera tidak mengikuti rekam jejak saudaranya, yaitu harimau Jawa.
Referensi:
Boomgaard, Peter. 1994. Death to the Tiger! The Development of Tiger and Leopard Rituals in Java, 1605-1906. South East Asia Research, 2(2), 141-175.
Lombard, Denys. 1996. Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
https://endangeredtigers.org/tiger-species/javan-tiger/#:~:text=They%20were%20forced%20into%20extinction,remote%20part%20of%20the%20island
https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5888/kenampakan-3-tiga-ekor-harimau-sumatera-di-taman-nasional-bukit-tiga-puluh#:~:text=Harimau%20Sumatera%20merupakan%20satwa%20dilindungi,jenis%20ini%20adalah%20Critically%20Endangered.
https://nationalgeographic.grid.id/read/13294141/harimau-jawa-punah-atau-tidak