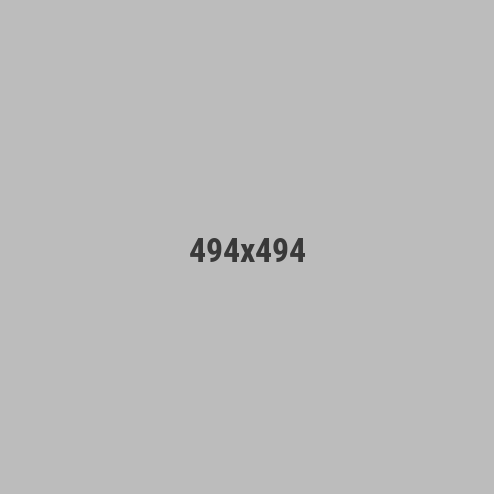
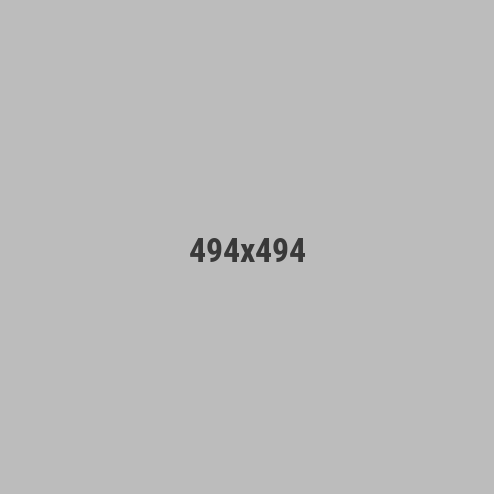

Foto aerial ladang milik warga di hutan Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Kamis (25/11/2021). ANTARAFOTO/Bayu Pratama S
Kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sejak 2018, pendapatan nasional dari ekspor minyak sawit melampaui pendapatan dari ekspor minyak bumi dan gas, dua komoditas yang selama ini menjadi penopang utama perolehan devisa negara.
Tercatat, berdasarkan data GAPKI (2023), pencapaian produksi CPO tahun 2022 mencapai 46,729 juta ton. Produksi ini lebih rendah dari produksi tahun 2021 sebesar 46,888 juta ton. Pencapaian tersebut merupakan penurunan berturut-turut selama 4 tahun terakhir sejak kelapa sawit diusahakan secara komersial di Indonesia.
Sebaliknya, konsumsi dalam negeri pada 2022, secara total mencapai 20,968 juta ton. Jumlahnya lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 18,422 juta ton.
Secara rinci, konsumsi tersebut didominasi industri pangan sebesar 9,941 juta ton. Konsumsi pada 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 8,954 juta ton dan lebih tinggi dari 2019 pada saat sebelum pandemi sebesar 9,860 juta ton.
Adapun konsumsi untuk industri oleokimia mencapai 2,185 juta ton. Jumlahnya meningkat 2,8% dibanding tahun 2021 sebesar 2,126 juta ton dan jauh lebih rendah dari kenaikan konsumsi 2019-2020 yang mencapai 25,4% dan 2018- 2019 sebesar 60%. Penurunan ini diduga berhubungan dengan situasi pandemi covid-19.
Di sektor energi, konsumsi CPO untuk biodiesel 2022 mencapai 8,842 juta ton. Konsumsi ini lebih tinggi dari konsumsi pada 2021 sebesar 7,342 juta ton. Sementara itu, ekspor 2022 sebesar 30,803 juta ton, lebih rendah dari tahun 2021 yang sebesar 33,674 juta ton, sekaligus tahun ke-4 berturut-turut menurunnya nilai ekspor yang terjadi dari tahun ke tahun.
Nilai ekspor CPO, olahan dan turunannya pada tahun 2022 mencapai US$ 39,28 miliar. Jumlahnya lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar US$ 35,5 miliar. Hal tersebut terjadi karena memang harga produk sawit tahun 2022 relatif lebih tinggi dibandingkan harga tahun 2021.
Meski mengalami penurunan, sektor sawit Indonesia telah berkontribusi terhadap 2,4 juta petani swadaya, 16 juta tenaga kerja. Industri ini juga dapat terus mendorong PDB di sektor perkebunan pada angka yang positif. Nilai PDB Indonesia di sektor ini pada Triwulan 3 tahun 2022 dapat bertumbuh positif di angka 5,72%.
Sebagai perbandingan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2023), sebagai induk industri kelapa sawit, industri agro tercatat tumbuh 3,90% pada Triwulan II – 2023 (year on year) dengan kontribusi terhadap PDB sektor non-migas mencapai 50,87%.
Kondisi tersebut menjadikan industri kelapa sawit menduduki peringkat pertama dalam kontribusi pertumbuhan sektor industri agro. Apalagi, industri hilir kelapa sawit memiliki komitmen untuk berkontribusi pada upaya global pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE). Hal ini membuat pemerintah menempatkan industri kelapa sawit sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Besarnya peran sektor sawit dalam menopang perekonomian nasional ternyata dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satunya, adanya perkebunan kelapa sawit atau lahan untuk perkebunan yang dikuasai perusahaan, perseorangan atau kelompok masyarakat yang berada secara ilegal di dalam kawasan hutan.
Tercatat, menurut KLHK, luas perkebunan sawit di kawasan hutan mencapai 3,37 juta hektar. Akibatnya, kebun sawit selalu dituding sebagai penyebab deforestasi dan tidak mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan. Padahal, perkebunan kelapa sawit juga mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Misalnya, pada perkebunan rakyat dengan total luas 6,72 juta hektar, perkebunan sawit rakyat menjadi sumber kehidupan utama 10,28 juta orang atau 8,53% penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan.

| Foto udara perkebunan kelapa sawit di Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (9/5 /2022). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berharap larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk-produk turunannya tidak berlangsung lama, karena akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem industri sawit nasional. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya |
Oleh karenanya, upaya penyelesaian konflik lahan perkebunan sawit di kawasan hutan sangat penting sebagai bagian dari upaya membangun iklim investasi sebagaimana amanat UU Cipta Kerja.
Dasar Regulasi
Menilik pada sejarahnya, sejak era Presiden Soeharto, Indonesia sudah dicanangkan menjadi produsen dan eksportir terbesar di dunia mengalahkan Malaysia. Ini dilakukan dengan meningkatkan luas perkebunan kelapa sawit menjadi dua kali lipat, atau 5,5 juta ha pada tahun 2000.
Menurut Wibowo et. al. (2019), sejak pencanangan itu daya tarik komoditas kelapa sawit meningkat seiring dengan meningkatnya harga minyak di pasar global. Sehingga memberi peluang semakin besarnya tekanan terhadap hutan, yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan.
Pengurangan luas hutan terjadi, baik melalui proses legal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, maupun akibat perluasan perkebunan kelapa sawit ilegal yang diketahui berada di dalam kawasan hutan. Perluasan perkebunan kelapa sawit ilegal tersebut telah memicu terjadinya beragam konflik, yang melibatkan antar pihak seperti masyarakat dan perusahaan, serta masyarakat dan pemerintah. Selain konflik, tumpang tindih antar penggunaan dan pemanfaatan lahan juga sering kali terjadi.
Hal ini menjadikan aspek legalitas penguasaan (tenurial) lahan merupakan aspek krusial yang menjadi bagian penting dari tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik. Selain itu, aspek legalitas lahan juga menjadi salah satu kendala penting di dalam proses sertifikasi minyak sawit berkelanjutan.
Permasalahan tidak jelasnya legalitas dan tenurial selama ini, baik yang dihadapi perusahaan maupun petani berimplikasi pada aspek kepastian berusaha, legalitas dan legitimasi produk-produk perkebunan yang dihasilkan. Akibatnya, penguasaan kawasan hutan secara ilegal dan tidak terselesaikannya permasalahan tenurial dapat berdampak pada hilangnya penerimaan negara dan terhambatnya akses bagi investor dan petani untuk meningkatkan produktivitasnya.
Terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengamanatkan dua klaster tipologi mengenai penyelesaian perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan.
Pertama, pada UU Ciptaker Pasal 110A menyebutkan perkebunan sawit yang telah terbangun, memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.
Kemudian, perkebunan sawit yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu hingga 2 November 2023, dikenai sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.
Kedua, UU Ciptaker Pasal 110B menyebutkan bahwa kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif; dan/atau paksaan pemerintah.
Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.
Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 menyebutkan bahwa pemilik kebun rakyat yang berada di Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui skema Perhutanan Sosial dalam jangka waktu tertentu atau disebut sebagai jangka benah.
Dalam kaitannya dengan jangka benah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 menyebutkan kegiatan jangka benah menggunakan tanaman pokok kehutanan sesuai silvikultur di sela-sela tanaman sawit tanpa melakukan penanaman sawit baru. Pada masa setelah habis 1 (satu) daur selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam sawit, maka pengelola wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan Hutan kepada negara.
Gagasan Model Jangka Benah
Selama ini, penyelesaian masalah sawit ilegal di kawasan hutan dapat dilakukan melalui tiga alternatif kebijakan, yaitu: (1) eksklusi, (2) legalisasi dan (3) jangka benah. Hanya saja, kebijakan eksklusi dilakukan dengan mengeluarkan tanaman sawit dari kawasan hutan. Pelaksanaan kebijakan ini rumit, berbiaya mahal dan rawan terjadi konflik sosial.
Begitu pula, kebijakan legalisasi yang dilakukan dengan cara menetapkan sawit sebagai tanaman hutan sehingga status kebun sawit berubah menjadi hutan sawit. Kebijakan ini dikhawatirkan meningkatkan ekspansi kebun sawit di kawasan hutan. Karenanya, saat ini, model jangka benah dapat dipandang sebagai kebijakan jalan tengah yang paling rasional dan mudah dilaksanakan dibanding dua kebijakan lainnya, dalam upaya penyelesaian konflik kebun sawit di kawasan hutan.
Jangka benah merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem sesuai tujuan pengelolaan. Jangka benah juga harus dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih ijin di Hutan Produksi.
Penerapan jangka benah dilakukan pada kawasan hutan yang terlanjur bersawit yang telah dibebani ijin Perhutanan Sosial. Berdasarkan Permen LHK Nomor 9/2021 menyebutkan pemanfaatan kebun rakyat dilakukan dalam bentuk kemitraan kehutanan atau kemitraan konservasi, Hutan Desa (HD), dan/atau Hutan Kemasyarakatan (Hkm).
Kebijakan jangka benah dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menanam minimal 100 pohon per hektar di antara tanaman sawit sehingga kebun sawit monokultur berubah menjadi wanatani sawit (agroforestri sawit).
Tahap kedua adalah menata wanatani sawit menjadi hutan tanaman. Penerapan kebijakan jangka benah ini memberi kesempatan kepada petani untuk memanen sawit selama jangka benah, sekaligus memberi legalitas kepada petani untuk mengelola hutan tanaman, melalui skema Perhutanan Sosial (Sudaryanti et. al., 2022).
Namun, pandangan para pakar terhadap jangka benah tahap kedua adalah beragam, yang tercermin dari tiga alternatif pilihan. Pada opsi pertama, semua pohon sawit ditebang. Sedangkan tanaman yang berupa pohon dipelihara dan bahkan ditanam untuk menggantikan pohon sawit yang ditebang. Wanatani sawit berubah sepenuhnya menjadi hutan tanaman yang tidak menghasilkan sawit.
Pada opsi kedua, wanatani sawit sederhana diubah menjadi wanatani kompleks. Hal ini dilakukan dengan menambah jenis dan jumlah tanaman wanatani. Pohon sawit tidak ditebang namun dipelihara bersama-sama dengan beragam jenis tanaman lainnya. Sedang pada opsi ketiga, wanatani sawit ditata sehingga memenuhi kaidah wanatani hutan tanaman, yaitu memiliki penutupan tajuk pohon > 40%, dan areal sawit < 40%. (Sudaryanti et. al., 2022; Puspitojati, 2011).
Dengan adanya berbagai instrumen kebijakan ini, penerapan jangka benah sebagai langkah penyelesaian keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan, diharapkan menjadi salah satu acuan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait, untuk berkontribusi dalam pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan.
*) Penulis merupakan peneliti dari Lembaga INRISE
Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Universitas Tanjung Pura (UNTAN) Kalimantan Barat tahun 2022 - 2023 yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Referensi:
[BPDPKS] Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 2023. Kinerja Sektor Sawit dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
[GAPKI] Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2023. Kinerja Industri Minyak Sawit 2022. Diakses dari: https://gapki.id/news/2023/01/25/kinerja-industri-minyak-sawit-2022/
Kementerian Perindustrian. 2023. Industri Hilir Sawit Siap Menuju Net Zero Emission. Diakses dari: https://www.kemenperin.go.id/artikel/24404/Industri-Hilir-Sawit-Siap-Menuju-Net-Zero-Emission#:~:text=Sebagai%20induk%20industri%20kelapa%20sawit,migas%20mencapai%2050%2C87%25.
Puspitojati, T. 2011. Persoalan Definisi Hutan dan Hasil Hutan Dalam Hubungannya Dengan Pengembangan HHBK melalui Hutan Tanaman. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 8 (3), Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Bogor.
Sudaryanti, D A, H Santoso dan Marhaento. 2022. Strategi Jangka Benah dan Penyelesaian Kebun Sawit di Dalam Kawasan Hutan. Information Brief. SPOS Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.
Wibowo L R, I Hakim, H Komarudin, D R Kurniasari, D Wicaksono, B Okarda. 2019. Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan untuk Kepastian Investasi dan Keadilan. Working Paper 247. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).