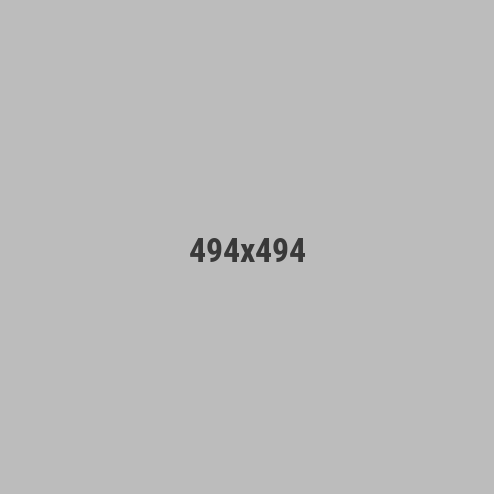
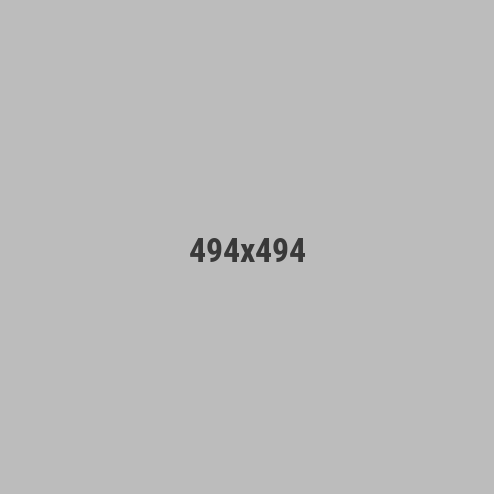

Ilustrasi FDI (Foreign Direct Investment) atau penanaman modal (investasi) dari luar negeri. Shutter stock/WESTOCK PRODUCTIONS
Peran investasi terlebih investasi asing langsung (FDI) dalam perekonomian sebuah negara, sudah lama diyakini sebagai salah satu faktor penting. Tidak terkecuali untuk Indonesia. Tak heran, sejak awal Orde Baru keran investasi untuk asing, telah dibuka lebar-lebar.
Iming-iming insentif pun negara berikan kepada para investor, agar mau berinvestasi di Indonesia. Namun, krisis 1997-98 menghancurkan banyak bisnis yang ditanam para investor asing.
Satu-persatu, mereka pergi meninggalkan Indonesia. Sebaliknya, China dan Vietnam semakin tumbuh sebagai salah satu negara tujuan investasi favorit bagi para investor.
Mobilitas Investasi Asing Global
Gangguan dalam investasi memang bertransformasi dalam beragam bentuk. Jika pada 1997-1998 lalu krisis monetar jadi penyebab, kini pandemi menjadi faktor merosotnya arus investasi. Menilik mobilitas modal di dunia, data World Invesment report 2023 menyebutkan, nilai FDI global di tahun 2022 turun 12,4% dibandingkan tahun 2021.
Jika pada 2021, nilai FDI di dunia mencapai US$1,45 triliun, setahun kemudian melorot menjadi US$1,3 triliun.
Penurunan investasi asing langsung terbesar terjadi pada kelompok negara-negara maju (developed countries), yaitu sebesar 37% menjadi hanya sebesar US$378 miliar. Sementara arus investasi asing langsung ke kelompok negara-negara berkembang, dilaporkan justru mengalami kenaikan sebesar 4% menjadi US916 miliar.
Berdasarkan kawasannya (region), maka arus masuk terbesar dari investasi asing langsung ditujukan ke Asia. Nilai arus masuk investasi asing langsung mencapai US$662 miliar. Nilai tersebut adalah 51% dari keseluruhan arus masuk FDI seluruh dunia. Nilai investasi asing tersebut tidak berubah dibandingkan tahun 2021
Meski demikian, pertumbuhan investasi asing langsung tertinggi, terjadi di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Pertumbuhan arus investasi tersebut mencapai 51% dari US$138 miliar di 2021 menjadi US$208 miliar di 2022.
Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, nilai investasi asing langsung yang masuk di tahun 2022 tercatat sebesar US$ 222,6 miliar. Dari jumlah tersebut, terbesar ditujukan ke Singapura sebesar US$141 milyar. Diikuti oleh Indonesia yang menerima investasi US$22 miliar, Vietnam sebesar US$18 miliar, serta Malaysia sebesar US$17 miliar.
Dengan besaran tersebut, nilai arus masuk investasi asing langsung ke kawasan Asia Tenggara tumbuh 4,6% dibandingkan tahun 2021. Arus investasi asing langsung ke kawasan ini sempat melonjak sebesar 79,4% di tahun 2021. Kondisi ini terjadi seiring dengan meredanya pandemi covid-19. Sebelumnya di tahun 2020, arus masuk investasi asing langsung ke Asia Tenggara mengalami pertumbuhan minus 29%.
Sebagai catatan, ketika terjadi krisis moneter yang diikuti krisis ekonomi di akhir dekade 1990-an, arus investasi asing yang masuk ke kawasan Asia Tenggara tercatat tumbuh minus. Tahun 1998, pertumbuhan FDI di kawasan ini mencapai (-41,8%). Di Indonesia endiri, pertumbuhan FDI bahkan mencapai (-104,4%).
Pertumbuhan ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Singapura saja hanya mengelami pertumbuhan (-62,1%) dan Malaysia sebesar (-57%). Sedangkan pertumbuhan FDI untuk Asia keseluruhan, mengalami (-16%).
Satu dekade kemudian, di tahun 2008, ketika terjadi krisis ekonomi global yang didahului oleh krisis subprime mortgage di AS, pertumbuhan arus masuk FDI di dunia mengalami minus 22%. Di kawasan Asia dan Asia Tenggara sendiri, dampak akibat krisis tersebut baru dirasakan di tahun 2009.
Ketika itu laju pertumbuhan arus masuk FDI ke Asia dan Asia Tenggara masing-masing mengalami (-15%). Indonesia sendiri bahkan mengalami pertumbuhan arus masuk FDI (-47,7%). Nilai arus masuk investasi asing langsung ke Indonesia tahun 2009 pun tinggal sebesar US$4,9 miliar. Sementara tahun 2008, nilainya masih sebesar US$9,3 miliar.
Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, laju pertumbuhan FDI Indonesia memang bukan yang terendah. Malaysia ketika itu tercatat mengalami laju pertumbuhan terendah, yaitu sebesar hampir (-80%). Kecuali Singapura, arus masuk FDI di tahun 2009 tersebut sudah kembali mengalami pertumbuhan sebesar 57%. Hal ini terjadi karena Singapura telah terdampak langsung di tahun 2008, di mana negara tersebut mengalami minus (-72,3%).

Investasi Asing di Indonesia
Dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia selama masa Orde Baru, peran investasi asing adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dimungkiri. Seperti banyak diketahui, ekonomi Indonesia di awal masa Orde Baru dibangun dari masuknya modal asing. Pemerintah Orba ketika memulai pemulihan ekonominya dengan mengeluarkan UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA).
Kebijakan tersebut pada dasarnya memang sangat beralasan. Kala itu, Indonesia tengah berada ditengah keterpurukan ekonomi yang sangat parah. Berbagai pendapat menyebutkan, melihat tingkat inflasi ekonomi Indonesia saat itu, sejatinya hiperinflasi sudah terjadi.
Hal Hill dalam bukunya The Indonesia Economy Since 1966, Southeast Asia's Emerging Giant (1996) mencatat, tingkat inflasi Indonesia sampai menjelang akhir dekade 1960-an telah berada di atas 500%. Bahkan secara lebih ekstrem Arief Budiman (1991) menyebutkan, antara tahun 1964-1965 tingkat inflasi Indonesia telah mencapai angka 732%.
Tingginya tingkat inflasi ini jelas sangat tidak akan menguntungkan bagi sebuah rezim baru yang akan menitikberatkan program-programnya, pada pembangunan dan peningkatan di bidang ekonomi.
Dalam konteks politik global, sebagai sebuah rezim yang anti komunis pada saat itu Orde Baru, jelas banyak mendapat dukungan dan kemudahan dari negara-negara Barat. Tentunya, untuk membiayai perbaikan ekonomi pada tahap awal, seperti pengendalian terhadap tingkat inflasi dan sebagainya.
Pihak Indonesia juga mendapat bantuan dari IMF dengan penjadwalan ulang (rescheduling) terhadap pembayaran hutang luar negeri.
Hal ini selanjutnya diikuti dengan pembentukan sebuah lembaga donor internasional IGGI (Inter-Govermental Group for Indonesia) yang dalam perkembangannya kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Consultative Group for Indonesia (CGI).
Pengembangan sistem ekonomi model kapitalistis pada masa awal Orde Baru, bisa dibilang menjadikan investasi asing sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang paling penting. Pemerintah Orde Baru menilai pembukaan kesempatan dalam skala besar bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk dapat memutar kembali roda perekonomian.
Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama mengapa pemerintah Orde Baru kemudian mengeluarkan kebijakan undang-undang, tentang penanaman modal asing (PMA) pada bulan Januari 1967.
Dalam konteks ini, Winters dalam Power in Motion(1996) mencatat penyataan Sadli mengenai UU PMA tersebut. M. Sadli menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan yang menyangkut pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia menawarkan perangsang dan jaminan.
Misalnya, menawarkan pembebasan pajak, penurunan tarif pada faktor-faktor produksi yang diimpor dan lain sebagainya. Meski demikian UU tersebut juga tidak secara tegas memberikan jaminan, pemerintah Indonesia tidak akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.
Di sisi lain, Winters juga mencatat, pada masa itu hanya ada dua kelompok investor swasta yang mempunyai sumber daya paling besar dan berpengalaman dalam produksi, yaitu investor transnasional dan penduduk keturunan Cina. Namun, alasan mengapa para investor asing yang pertama menjadi perhatian, adalah karena pada waktu itu rasa permusuhan terhadap etnis Cina masih sangat tinggi.
Memang, dalam kerangka besar pembangunan lima tahunan (Pelita), pemerintah pada masa itu mengeluarkan kebijakan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada pembangunan sektor industri nasional yang didasarkan pada sumber-sumber utama, seperti baja, gas alam, pengeboran minyak dan alumunium. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga mulai mengambangkan berbagai industri manufaktur lain sebagai bagian dari kebijakan industri substitusi impor.

Kapitalisme Semu
Sayangnya, seiring dengan tumbuhnya investasi ini, semakin marak pula praktik-praktik patronase bisnis. Celakanya lagi praktik-praktek tersebut kemudian semakin meluas ketika negara Orde Baru kemudian mendapatkan rezeki dari naiknya harga minyak mentah dunia. Akibatnya, yang tercipta justru adalah sebuah sistem kapitalis yang oleh Yoshihara Kunio diistilahkan sebagai ersatz capitalism (kapitalisme semu).
Bagi Kunio ada dua hal yang menyebabkan timbulnya kapitalisme semu tersebut. Pertama ialah karena di negara-negara tersebut peran pemerintah begitu besar, sehingga mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat kapitalisme menjadi tidak dinamis. Hal negatif lain yang ditimbulkan dari besarnya peran pemerintah atau negara ini ialah, adanya pencari rente di kalangan birokrat yang secara langsung dapat menghambat perkembangan para usahawan sejati.
Kedua ialah, sebuah bentuk kapitalisme yang tidak didasarkan pada perkembangan teknologi yang memadai. Artinya, proses trasformasi struktural berjalan tanpa dibarengi pengembangan industri yang berbasis pada sebuah industri domestik yang benar-benar tumbuh dari dalam. Inilah sebenarnya salah satu konsekuensi dari apa yang disebut dengan “alih teknologi”.
Di satu sisi, fenomena investasi asing langsung melalui berbagai perusahaan multinasional, diharapkan dapat memicu proses industrialisasi di berbagai negara-negara. Namun di sisi lain, hal tersebut perlu dibarengi sebuah pembentukan kelompok pengusaha dalam negeri atau dalam analisis kelas, sering diistilahkan sebagai kelas kapitalis domestik yang kuat.
Jika tidak, hal tersebut justru hanya akan menciptakan ketergantungan ekonomi pada investasi asing. Dampaknya adalah seperti yang dirasakan oleh Indonesia pada masa krisis. Karenanya, mobilitas modal asing tinggi mengakibatkan negara mau tidak mau harus bisa memberikan jaminan investasi bagi investor asing untuk tetap mau berinvestasi.
Mimpi Alih Teknologi
Pada dasarnya pembentukan kapitalis domestik sejati haruslah dimulai dari tingkat penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi inilah yang seringkali diabaikan, ketika invetasi asing mulai masuk ke sebuah negara. Terminologi “alih teknologi” seringkali dipahami sebatas penggunaan atau penerapan atas teknologi itu sendiri.
Celakanya, hal tersebut seringkali tidak dibarengi oleh pengembangan dari teknologi tersebut di sini. Aspek inilah yang kemudian dalam teori-teori ekonomi industri, disebut dengan penelitian dan pengembangan (R&D). Terlebih, di era teknologi digital yang berkembang sangat cepat dan pesat di perempat pertama abad 21 ini.
Padahal, seharusnya penanaman modal asing adalah mekanisme yang cukup efektif untuk pengembangan sebuah teknologi. Dorongan hilirisasi di berbagai sektor dalam tahun-tahun terakhir pemerintahan Jokowi, sebenarnya adalah masa-masa yang harus dimanfaatkan untuk mencapai mimpi alih teknologi tersebut di Tanah Air.
Dengan begitu, kita tidak perlu lagi menghadapi berbagai persoalan yang oleh J.H Boeke(1983) disebut sebagai era prakapitalisme.
Referensi
Budiman, Arief, Negara Dan Pembangunan, Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan, Jakarta, Yayasan Padi dan Kapas, 1991.
Boeke, J.H; Projosisworo, D. (1983). Prakapitalisme di Asia / oleh J.H. Boeke ; penerjemah, D. Projosiswoyo. Jakarta :: Sinar Harapan,.
Hill, Hal, The Indonesia Economy Since 1966, Southeast Asia's Emerging Giant, Melbourne, Cambridge University Press, 1996.
Kunio, Yoshihara, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, Jakarta, LP3ES, 1991.
UNCTAD, World Investment Report 2023: Investing in sustainable energi for all, July 2023
Winters, J. A. (1996). Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State. Cornell University Press.